Penguatan Pendidikan Islam
Menarik mencermati tulisan Abuddin Nata tentang Tantangan Pendidikan Islam, dia menilai
bahwa pendidikan Islam zaman sekarang selain menghadapi pertarungan
ideologi-ideologi besar dunia juga menghadapi berbagai kecenderungan tak
ubahnya seperti badai besar (turbulance)
atau tsunami (Republika, 24 Maret 2009). Memang, persoalan pendidikan Islam
selalu menarik diperbincangkan secara akademik dalam upaya mencari formulasi
alternatif bagi sistem pendidikan yang dalam batasan tertentu dianggap kurang
akomodatif terhadap kebutuhan pendidikan Islam.
Konsep pendidikan barat, yang selama ini ditawarkan
dan telah berurat berakar dipraktekkan di hampir seluruh dunia muslim,
nampaknya belum secara massif berhasil
“mencerahkan”. Demikian juga dengan usaha memperkenalkan sistem pendidikan
Islam pada tataran pragmatis masih menyiratkan beberapa kerancuan. Institusi
sekolah Islam misalnya, sampai saat ini dapat ditemukan nuansa yang kental
dengan dualisme atau dikotomisme pendidikan. Sehingga pada konteks pelaksanaan
pengajaran, lembaga sekolah Islam terkesan hanya berpretensi untuk mengajarkan
aspek disiplin keilmuan agama (religious
sciences), dengan memberi porsi yang sangat minim terhadap
penelaahan ilmu-ilmu umum (secular sciences).
Seperti halnya dalam konteks pendidikan Islam di
Indonesia, untuk memahami terma “pendidikan Islam”, setidak-tidaknya terdapat
perbedaan makna dan orientasi. Pertama, yang
dimaksud dengan pendidikan Islam adalah tradisi pengajaran Islam yang sudah
lama berlaku di masyarakat seperti pesantren, baik yang diselenggarakan oleh
organisasi Nahdhatul Ulama maupun Muhammadiyah. Kedua, pendidikan Islam juga sering diidentikkan dengan
lembaga madrasah yang sekarang terus mengalami perbaikan konsepnya. Ketiga, istilah pendidikan Islam juga
tidak jarang dipahami sebagai sebuah konsep pendidikan.
Munculnya realitas seperti itu, menurut Hasan Langgulung (1989) sebagai akibat dari penataan pendidikan Islam tidak mengakar pada sumber ajaran ke-Islam-an. Sesungguhnya, Islam selalu menempatkan semua kajian keilmuan dalam posisi yang mulia selama diarahkan untuk memahami rahasia Allah dan dikembangkan bagi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu deskripsi ketidakutuhan paradigma pendidikan Islam selama ini, terutama dalam bentuk dikotomisme sangat mempengaruhi rancang-bangun kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam yang ditata atas konsep dasar (philosophical concept) yang rapuh ini, tentu berkonsekuensi semakin terlihatnya inferioritas di kalangan muslim dengan kecendrungan kurang mampu mengakses perkembangan ilmu pengetahuan mutakhir dan kemajuan teknologi. Fenomena ini menurut Mastuhu (1999) disebabkan kurikulum pendidikan Islam yang terkait dengan pendekatan pengajaran (teaching approach) yang kaku, masih menekankan pada tradisi hapalan, dogmatis, dan ritual.
Dalam perspektif historis, menurut Azyumardi Azra
(1998), dengan mengambil kasus perkembangan intelektualisme Islam di era
Baghdad, kurikulum pendidikan Islam sejak lama terkesan kurang akomodatif
terhadap nuansa eksakta (natural sciences).
Tekanan aktivitas pengajaran baik di Kuttab, Masjid, dan Madrasah menunjukkan
beberapa pokok kajian seperti; materi filologi, grammar, rethoric, literatur,
tafsir al Qur’an, ilmu qiraat, hadist, fiqh, faraidh, dan ilmu kalam (teologi).
Dimana faktor penyebab terjadinya kondisi di atas
adalah, secara internal, pada kaum muslim muncul kecenderungan lebih menganggap
utama gaya hidup sufisme, sehingga kajian yang bersifat progressive dipandang hanya akan
mendangkalkan aqidah dan kurang bermanfaat di akhirat. Dan secara eksternal,
dibumihanguskannya khazanah intelektual Islam di Baghdad sejak mengalami puncak
kegemilangan dari tahun 750-1250 M oleh pasukan Mongol semakin mempercepat
runtuhnya tradisi ilmiah kaum muslim. Mulai dari keruntuhan khazanah Baghdad
inilah fenomena pendidikan Islam semakin menunjukkan gejala yang kurang
akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan penalaran yang bersifat rasionalistik-empirik-radikal. Seperti
kebanyakan madrasah pedesaan di Indonesia, secara material lebih bercoral fiqh oriented meskipun telah
mengakomodasi metode belajar yang dialogis. Kondisi ini berlanjut sedemikian
rupa, sehingga pada akhirnya kalangan muslim mengalami keadaan yang dinamakan cultural and intelektual shock yang di
satu sisi mengharuskan kaum muslim menginternalisasi ajaran-ajaran normatif
Islam, tetapi di lain sisi kaum muslim diharuskan menyesuaikan diri dengan
perkembangan konsep pendidikan Barat yang sekuler. Realitas seperti ini tidak
ayal lagi mengakibatkan semakin cepat berkembangnya konsep dualisme dalam
pendidikan Islam.
Dualisme, atau yang sering disebut juga dengan
dikotomisme, dalam pendidikan Islam adalah kondisi paradoksal yang terjadi
dalam pelaksanaan pendidikan yang berakhir pada pemisahan subjek kajian yang
disebut sebagai islami dan tidak islami terhadap disiplin keilmuan dalam
pendidikan. Sehingga dalam skala pragmatis sekolah Islam cenderung tidak
memberi ruang yang besar terhadap kajian yang diberi label dengan “ilmu-ilmu
umum”. Padahal menurut al-Faruqi seperti dikutip al-Baghader untuk yang satu
ini belum satupun universitas Islam yang dapat mengklaim bahwa kurikulum yang
mereka tawarkan bersifat Islami.
Hal senada juga dikatakan oleh Joseph S. Sayliowich
dalam bukunya Educatioan and Modernisation
in The Middle East (1973), dia melihat kondisi pendidikan dan
kultur umat Islam, bahwa freedom of thought
bukan menjadi nilai utama pada masyarakat Islam, sehingga
pembenahan dimensi pendidikan dan budaya harus merupakan refleksi dari
persoalan ini. Tesis Sayliowich ini setidaknya merupakan gambaran wacana
pendidikan Islam pasca keunggulan Islam dan berlaku untuk sekarang sejak
beberapa kurun waktu yang cukup lama.
Kenyataan dikotomi dalam pendidikan Islam tidak lebih merupakan akibat distorsi dari konsep pendidikan luar (Eropa Barat) yang nota benenya bukan berasal dari konsep qur’ani. Kecenderungan pelaksanaan pendidikan Islam yang tidak berorientasi pada pengembangan nalar dan potensi rasionalitas, tetapi justru diarahkan pada hal-hal yang abstrak dan sulit diterima akal sesungguhnya telah benar-benar terjadi. Dalam pada itu, kata Ismail Raji’ al-Faruqi (2000), tidak mengherankan bila universitas kaum muslimin memiliki standar yang rendah, dan selalu tergantung kepada Barat dalam hal pendidikannya.
Fenomena ini, seharusnya segera dicermati karena
lebih berpotensi pemperlemah kualitas pendidikan Islam. Ada dua hal yang harus
dilakukan sebagai langkah penguatan terhadap konsep pendidikan Islam. Pertama, penguatan atas kemampuan konsep
qur’ani dalam menata sistem pendidikan Islam masa depan. Pengakuan ini penting
sebagai landasan moral untuk menggali nilai-nilai esensi dari anggitan ilahi. Kedua, kemampuan untuk terus
mensosialisasikan nilai-nilai moralitas dan dasar konsep islami kepada publik
melalui berbagai media dan kesempatan. Sebab di antara penyebab kurang
dipahaminya konsep Islam khususnya dalam tataran pendidikan adalah konsekwensi
dari kurangnya sosialisasi konsep ini, termasuk di kalangan muslim sendiri,
sehingga sampai sekarang kaum muslim tidak memiliki visi yang utuh dan seragam mengenai
konsep kefilsafatan atau epistemologi pendidikan Islam.
Oleh karena itu harus dipahami bahwa corak pendidikan
Islam berada pada dua kutub dengan kecendrungan masing-masing sebagai akibat
tidak dimilikinya visi dan tidak dipahaminya konsep filosofis pendidikan Islam.
Itulah sebabnya kata al-Faruqi saat ini terdapat perbedaan antara kecenderungan
pendidikan yang berorientasi pada Islam sciptural-normatif
dengan yang mempunyai kecenderungan diskriptik-empirik. Walaupun pada dasarnya jika dipahami
konsep dasar filsafat pendidikan Islam pertentangan tajam dan saling merugikan
antara kedua kecendrungan itu tidak perlu terjadi. Dalam kaitan itu Fazlur
Rahman pernah mensinyalir bahwa persoalan intelektualisme Islam sampai kini
masih memburuk, dalam bentuk perlakukan yang ad
hoc (sepotong-sepotong) dan terkadang amat intrinsik terhadap
konsel al Qur’an.
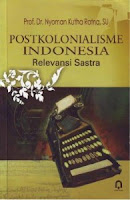

Komentar