Kembali Bisnis Buku Sekolah
Persoalan buku pelajaran bagi murid SD-SLTA di
Indonesia selalu muncul setiap dimulainya tahun ajaran baru. Ketika masih
memakai sistem caturwulan, buku pelajaran menjadi masalah setiap caturwulan.
Akar masalahnya tidak lain karena setiapcatur wulan/semester buku pegangan
murid harus ganti. Setelah itu buku pelajaran harus diganti karena tidak bisa
digunakan lagi oleh adik kelas pada tahun yang akan datang. Dengan kata lain,
penggunaan buku-buku pelajaran kita amat tidak efisien, efektif, dan
membodohkan.
Bisnis buku semacam itu sudah berlangsung selama
hampir tiga dekade terakhir, tetapi hingga kini tidak ada penyelesaian yang
jelas. Para birokrat pendidikan justru melemparkan tanggung jawab dengan alasan
bahwa sekarang sudah otonomi daerah sehingga daerah/sekolah bebas menentukan
jenis buku pegangan sendiri, tanpa campur tangan menteri atau Dirjen Pendidikan
Dasar dan Menengah.
Secara yuridis memang betul demikian karena
undang-undangnya mengatur pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, termasuk
dalam bidang pendidikan. Akan tetapi secara sosiologis, hal itu kurang tepat
karena faktanya ketergantungan birokrat daerah terhadap pusat masih cukup
besar. Kecuali itu, keberadaan Menteri Pendidikan sendiri dimaksudkan sebagai
kontrol terhadap jalannya pendidikan. Jika Menteri Pendidikan lepas tanggung
jawab mengenai buku-buku yang membebani dan membodohkan masyarakat, mengapa
harus ada Menteri Pendidikan?
Selain masalah sering berganti buku setiap semester
atau batas pemakaian yang terlalu pendek, masalah lain yang ditemukan dalam
buku pelajaran adalah isi dan corak buku itu sendiri, distribusi, harga beli,
serta kualitas.
Pergantian kurikulum satu ke kurikulum lain, termasuk
dari Kurikulum 1994, 2004, menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
2006, tidak otomatis membawa perubahan corak dan isi buku pelajaran secara
radikal, tetapi hanya tambal sulam. Hal ini disebabkan para penulis buku
sendiri banyak yang tidak memahami substansi KTSP. Dengan demikian yang
membedakan buku pelajaran menurut Kurikulum 2004, dengan buku pelajaran menurut
Kurikulum 2006 adalah pada sampul buku pelajaran Kurikulum 2004 ada tempelan
tulisan “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan”. Akan tetapi, jika dibaca secara
cermat, isinya tidak jauh berbeda dengan buku-buku pelajaran sebelumnya.
Ironisnya, meski corak dan isi buku itu buruk dan
menyesatkan, tetapi masyarakat dipaksa membayar mahal karena setiap semester
buku itu harus ganti dan harus dibeli dengan harga tinggi. Keharusan membeli
itu terjadi karena model penjualan buku-buku pelajaran itu memakai jalur
birokrasi pendidikan. Rata-rata tiap keluarga mengeluarkan uang antara Rp
200.000 hingga Rp 450.000 per anak per semester. Pembelian buku pelajaran
semacam itu menjadi masalah besar bagi keluarga yang memiliki anak lebih dari
satu dan bersekolah semua dan kebetulan berasal dari keluarga miskin. Sebab,
kebutuhan untuk membeli buku pelajaran saja minimal Rp 900.000 per semester.
Belum lagi kebutuhan buku-buku penunjang lainnya. Lebih ironis lagi karena
pemerintah sebetulnya mengeluarkan anggaran cukup besar untuk pendidikan tahun
ini. Ke mana larinya buku-buku yang dibiayai oleh negara itu jika masyarakat
masih harus membeli dengan harga mahal?
Masalah lain adalah kualitas buku pelajaran yang
menjadi pegangan anak-anak secara objektif dinilai buruk, bahkan menurut Utomo
Dananjaya dari Institute of Education Reform (IER), kualitas buku-buku
pelajaran yang banyak dipakai oleh sekolah itu di bawah standar. Selain kurang
memperlihatkan penalaran yang baik, materi dalam buku itu juga banyak yang
tidak memiliki koherensi antara meteri satu dan lainnya sehingga seakan-akan
merupakan materi yang saling terpisah. Padahal, sebuah buku mestinya mengandung
suatu pemikiran yang utuh sehingga membantu mempermudah pembacanya untuk
mengerti.
Pengadaan buku yang dilakukan secara sentralistik
juga tidak mencerminkan kondisi lokal sehingga buku itu mengandung kesalahan
yang dapat menimbulkan rasa tidak hormat pada penulisnya. Satu contoh yang
sering kita baca pada pelajaran ilmu geografi adalah tentang musim di Indonesia
yang dibedakan dua musim, yaitu panas dan hujan. Namun, apabila kita pergi ke
Papua-yang masih menjadi bagian dari negara Republik Indonesia, di sana tidak
begitu jelas pembedaan musim itu karena sepanjang tahun hujan dan panas tidak
bermusim, tetapi selalu datang sewaktu-waktu. Materi yang demikian jelas
mencerabut pikiran anak-anak dari pengetahuan empiris mereka.
Lebih menyedihkan
lagi adalah materi buku-buku pelajaran agama yang sering kali justru
menciptakan segregasi murid berdasar agama yang dianutnya. Padalah, sekolah
seharusnya merupakan institusi tempat berseminya benih-benih kemanusiaan
terlepas dari agama yang dianutnya. Karena itu, merupakan hal yang tragis jika
ada teks buku yang mengajarkan murid pemeluk agama tertentu tidak boleh
mengucapkan selamat hari raya kepada pemeluk agama lain. Di lain pihak,
anak-anak menyaksikan orang-orang di sekitarnya saling menghormati dan
mengucapkan selamat hari raya kepada mereka yang merayakan hari raya keagamaan.
Munculnya cara
berpikir masyarakat yang linier, otoritatif, bahkan kadang dogmatis itu tidak
lepas dari interaksi dengan buku-buku pelajaran yang mereka konsumsi selama
bersekolah. Karena buku-buku pelajaran itu ditulis dengan menggunakan cara
berpikir yang linier, mengandalkan otoritas, dan bersifat dogmatis, maka secara
otomatis pikiran anak-anak yang membacanya juga terkontaminasi. Dan karena
proses kontaminasi itu berlangsung sekurang-kurangnya 12 tahun, hal itu
kemudian mengkristal dan terinternalisasi dalam diri anak.
Yang menyedihkan
lagi ada teks pelajaran agama yang secara eksplisit melarang penganut agama itu
mengucapkan selamat hari raya bagi pemeluk agama lain. Teks semacam ini selain
mengajarkan kepada anak tentang realitas bangsa yang majemuk, bisa juga
menggiring anak-anak membentuk komunitas eksklusif yang didasarkan pada agama
yang dianutnya. Teks-teks buku semacam itu sebetulnya lebih bersifat
indoktrinatif daripada mencerdaskan. Padahal, pendidikan itu hendaknya mampu
mencerdaskan orang-orang yang ada di dalamnya.
Bagi pelajar dan
orang tua, persoalan kualitas tidak hanya menyangkut soal isi buku itu, tetapi
juga secara fisik. Banyak buku pelajaran, terutama untuk SD, yang tidak dijilid
bagus sehingga mudah lepas sehingga merepotkon murid atau orang tua murid. Ini
kelihatannya sepele, tetapi bisa menjadi penghambat belajar bagi anak-anak
karena selalu merasa jengkel dengan bukunya yang sering lepas. Lagi pula, usia
anak-anak SD sebaiknya tidak dibebani dengan hal yang kecil-kecil dan terlalu
ruwet.
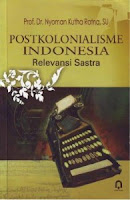

Komentar