Politik Damai Menuju Perbaikan Nasional
Sejarah politik di negeri kita memang penuh konflik
dan kering etika. Kebencian, balas dendam, dan penghimpunan kekuatan dengan
segala cara untuk mengawasi lawan menjadi bagian dari budaya elite politik dan
masyarakat. Jarang ditemukan perwujudan nilai-nilai politik yang santun seperti
toleransi, pemberian maaf, serta penghargaan terhadap hukum dan keadilan.
Keretakan yang sudah terlanjur seakan sulit diperbaiki. Dalam konteks ini,
Forum Rembuk Nasional dan wahana-wahana sejenis menuju islah nasional harus terus
dikembangkan.
Prasangka sosial (social
prejudices) adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap masih
munculnya konflik baik konflik antar-elite maupun horizontal. Masing-masing
berusaha mempertahankan identitas seraya tidak mengakui dan bahkan berusaha
menghilangkan identitas orang lain. Mereka enggan berinisiatif melakukan
komunikasi politik, dan selalu berada dalam tempurung kelompoknya, seraya
menjegal dan memberanguskan tempurung-tempurung kelompok lainnya. Identitas
kelompok ibarat pisau bermata dua: mempertahankan eksistensi diri sambil
berusaha menghilangkan eksistensi kelompok lain.
Ketika terjadi peralihan rezim, selalu muncul masalah
bagaimana menyikapi masa lalu. Apa yang seharusnya terjadi pada pelaku
kesalahan masa lalu? Di sebagian negara para domistik, ataupun pengadilan
internasional. Sebagaian pelaku kejahatan dibuang keluar negeri. Dan, di
beberapa negara komisi kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk, bertugas mencari
dan kemudian mengakui fakta-fakta yang benar.
Pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi,
menurut Peter R. Baehr, memang kontroversial. Di satu sisi, ada kalangan yang
lebih suka kebijakan memaafkan, melupakan dan berpendapat bahwa proses ini akan
terganggu oleh pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi itu. Di sisi lain,
muncul gagasan bahwa pemberian maaf yang benar hanya mungkin setelah adanya
pengakuan atas fakta-fakta tersebut.
Dari perspektif etika politik, pengampunan politik
sesungguhnya diperlukan dalam kerangka rekonsiliasi menuju Indonesia Baru.
Sikap pemaaf dalam konteks politik adalah tindakan yang menggabungkan kebenaran
moral, kesabaran dan pengendalian, serta komitmen untuk memperbaiki hubungan
yang retak. Ini tidak berarti mengabaikan begitu saja kejahatan masa lalu dan
mengabaikan keadilan. Tindakan hukuman yang adil jelas diperlukan untuk
mengetahui apakah mereka itu bersalah ataukah tidak. Islah nasional diperlukan
setelah proses hukum dijalankan.
Indonesia baru hanya bisa diraih melalui suatu upaya
rekonsiliasi seluruh elemen bangsa. Harus ada komitmen bahwa rekonsiliasi
merupakan tugas mulia. Tidak ada wacana yang lebih baik daripada mengajak
dengan komitmen yang tulus kepada kebaikan dan perdamaian antarmanusia. (An-Nisa’: 144). Konflik dan friksi yang
selama ini terjadi harus mampu diatasi melalui kerja islah politik nasional.
“Jika terjadi konflik antara dua golongan dari orang-orang beriman, maka
damaikanlah mereka.” (Al-Hujarat:
9).
Tanpa upaya islah, bangsa ini akan berjalan tanpa
arah. Tanpa islah, sulit ditemukan strategi yang mujarab untuk mengatasi
masalah bangsa yang kompleks ini. Bangsa ini benar-benar membutuhkan
transformasi sosial ke arah yang lebih sejahtera dan damai. Padahal, perubahan
sosial yang genuine, seperti
dikatakan Hannah Arendt (1959), hanya dapat dilahirkan oleh dua kemampuan:
memaafkan dan membuat kesepakatan yang baru. Salah satu sebab mengapa suatu
kesepakatan yang baru sulit dicapai adalah keengganan para pemimpin politik
untuk saling memaafkan dan mengampuni cinta dan pemberian maaf dalam konteks
politik belum menjadi kamus politik para pemimpin kita, sementara benci dan
balas dendam seakan telah membudaya.
Dalam konteks inilah, sikap dan tindakan memaafkan
menjadi penting untuk memperbaharui suatu hubungan kemanusiaan dan memperbaiki
retak-retak permusuhan yang sudah terlanjur terjadi dimasa lalu.
Memaafkan dalam konteks politik, seperti dikatakan
Donald W. Shriver dalam An Ethics for
Enemies: Forgiveness in Politics (1995), bukanlah ‘melupakan’ masa
lalu begitu saja, tapi justru mengingatnya kembali dan baru kemudian memaafkan.
Dalam proses ini diperlukan upaya mengingat fakta-fakta masa lalu dan melakukan
penilaian moral secara jujur terhadap kesalahan, ketidakadilan, dan luka masa
lalu itu.
Pengampunan dalam konteks politik tindakan berarti
membebaskan hukuman terhadap pelaku kejahatan masa lalu, tetapi berarti bebas
dari tindakan balas dendam. Pengampunan dimulai dari suatu dorongan ‘penilaian
moral’ dan pengendalian dari rasa dendam. Pengendalian rasa dendam akan membuka
pintu menuju masa depan yang tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Tanpa
ada pengendaliuan ini, suatu penilaian moral justru dapat menimbulkan
permusuhan baru.
Begitu pula perlu adanya empati terhadap sisi
kemanusiaan politik. Sikap empati ini diperlukan untuk tidak melihat perbedaan
secara negatif, tetapi melihatnya secara positif yaitu yang positif dan
konstruktif. Sikap empati dilakukan terhadap kesejatian orang lain, bahwa orang
lain memiliki hak yang sama untuk hidup secara damai dan membangun kehidupan
bersama yang rukun.
Dalam konteks ini, ada teladan menarik dari kisah
Nabi Yusuf. Kisah ini merupakan babakan dalam sejarah tentang persaingan,
dominasi, tipu daya, dan alienasi dalam keluarga. Tidak sekedar kisah dari
keluarga, tetapi lebih merupakan kisah bagaimana komunitas manusia dapat
tinggal dan mengatasi serangan-serangan lawan dengan berbagai cara.
Ketika Nabi Yusuf dan adiknya, Benyamin, mendapat
status lebih terhormat di sisi ayahnya, Yakub, dan saudara-saudaranya tahu
bahwa ayah mereka lebih mencintai Yusuf daripada saudara-saudaranya, mereka
membencinya. Namun, setelah meraih kesuksesan, Yusuf mampu melupakan dendam,
kebencian dan penderitaan di masa lalu.
Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan bagaimana sikap
pemaaf terhadap lawan politiknya. Ketika baru saja memperoleh kemenangan atas
Mekah, lawan-lawan politiknya yang pernah berusaha membunuhnya, segera
dimaafkan dengan mengatakan, “Pergilah! Kalian semua bebas.” Seakan Nabi
berujar, “Biarlah yang lalu biar berlalu”, sekarang mari kita buka lembaran
baru menuju masyarakat baru yang rukun dan damai.”
Dalam wacana teologis, manusia berhak mendapatkan
pengampunan Tuhan. Namun, menyangkut hubungan sesama manusia, pengampunan Tuhan
tidak dapat dicapai tanpa adanya pengampunan manusia. Tuhan memiliki sifat
pemaaf dan pengampun terhadap hamba-Nya yang berbuat dosa dan berkomitmen untuk
memperbaiki diri. Tuhan mengatakan “Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
memaafkan dengan orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. 31:134). Sudah
semestinya kita dapat mencontoh sifat-sifat Tuhan ini, seperti dikatakan Nabi
Muhammad SAW, “Berakhlaklah kalian seperti akhlak Tuhan.”
Kini seluruh komponen bangsa perlu pertama, menanamkan budaya toleran
melalui dialog yang efektif. Kedua, memaafkan
masa lalu dan membuka kesempatan yang baru. Ketiga,
berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup akrab.
Bukankah alasan salah satu wacana publik tentang
isu-isu konflik adalah tercapainya sikap saling menghargai setiap kepentingan
yang berbeda-beda? Mampukah kita mewujudkan dunia politik kita berjalan lebih
damai? Bukankah perwujudan etika politik yang santun merupakan prasyarat bagi
terciptanya rekonsiliasi bangsa? Dan, bukankah rekonsiliasi adalah prasyarat
bagi terwujudnya Indonesia baru yang dicita-citakan.
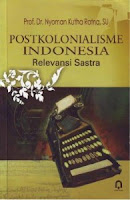

Komentar