Etika, Politik dan Postmodernisme
Judul Buku : Postmodernisme
Penulis : Kevin O’donnell
Penerbit : Kanisius
Cetakan : Pertama, 2009
Tebal : 164 halaman
Para filsuf berusaha mendasarkan etika pada masyarakat atau pada jiwa
rasional. Etika merepresentasikan tradisi sosial, yang membentuk dan membimbing
kita, atau ditulis ke dalam bangunan alam semesta dan dapat dilihat dalam hati
nurani individu sebagai sesuatu yang terberi.
Aristoteles mensugestikan bahwa etika merupakan hasil dari hidup dalam
masyarakat. Orang yang baik adalah orang yang menyumbangkan keterampilannya dan
bekerja sama. Keutamaan dikembangkan dan menjadi kebiasaan. Namun, Sokrates
mengusik manusia untuk mempertanyakan nilai dan hukum negara. Hal-hal ini harus
didasarkan pada rasio, bukan pada permainan kekuasaan dan prasikap, supaya adil
dan benar, dan karena itu layak disepakati.
Etika dalam tradisi ini, lebih merupakan urusan internal dan reflektif, yang
mencari penyelesaian yang rasional dan paling jelas. Konflik antara kedua
posisi ini disebut perbedaan antara ‘yang ada-dan yang seharusnya’.
Para penganut utilitarisme berpendapat bahwa yang ‘baik’ adalah yang dapat
dikerjakan dalam tiap situasi, sekaligus memperhitungkan pro dan kontra. Semboyan
mereka adalah ‘kebaikan terbesar dari sebagian besar rakyat’. Akibat turut
diperhitungkan, bukan hanya motif. Kerena itu, etika ditentukan secara sosial
dan pada keadaan aslinya, walau ada petunjuk umum/peraturan yang dapat
diterapkan. Tetapi dapatkah kita selalu mengaktualisasikan etika dengan
berhasil, apabila kita berurusan dengan manusia riil dan perasaannya?
Immanuel Kant berpendapat bahwa ada kemutlakan moral; ada hal yang selalu
benar atau salah, tanpa mempedulikan situasi. Ia menamakan ini imperatif
kategoris. Jadi, mencuri selalu ingat diri dan menipu selalu salah. Tetapi apa
yang terjadi kalau penipu dapat melindungi seseorang yang tidak bersalah dari
polisi rahasia? Siapa yang menentukan yang benar?
Postmodernisme menggoyang teori-teori besar, dan upaya untuk mendasarkan
etika pada ‘kebenaran’ tetap, tetapi ia juga memberikan sumbangan yang riil. Para
filsuf postmodern menekankan bagaimana realitas itu bersifat kemasyarakatan dan
relasional.
Dalam buku Postmodernisme ini, Kevin O’donnell melakukan penelitian
historis tentang asal usul dan pertumbuhan moralitas. Ia melacak pergeseran
fundamental sampai sebelum era kekristenan, sekaligus mempertentangkannya
dengan periode klasik. Yang ‘baik’ pada awal dihubungkan dengan yang kuat dan
berkuasa, kaum bangsawan.
Kekristenan mengangkat nilai kerakyatan orang kecil atau hamba. Etika
‘belas kasih’ dimasukkan, dengan perasaan kasih sayang kepada orang miskin dan
lemah. Inilah batu sendi etika Barat, namun demikian Kevin memandang bahwa hal
ini pada akhirnya menganut pendirian antikehidupan, karena ia berjuang melawan
ego, melawan perkembangan diri dan kesadaran. Memberi diri Anda sendiri menjadi
keutamaan, dan bukannya mengembangkan diri. Keberanian menjadi kesombongan, kebanggaan
menjadi cinta diri, dan kesehatan direndahkan demi nilai penderitaan, yang
‘baik bagi jiwa’.
Etika Postmodern?
Mungkinkah etika dalam pemikiran postmodern, dimana semua yang pasti dan
otiritas dipertanyakan? Jenis politik manakah yang mungkin, di balik anarkisme
atau quietisme dan kemasabodohan?
Bagi para postmodernis, semua adalah tafsiran, yang dibuat melalui indra
konseptual manusiawi kita. Realitas apa adanya, kebenaran dalam kemurniannya, tidak
dapat hadir di depan kita. Itulah keadaan manusia atau keadaan postmodern. Sering
hal ini dipahami sebagai lengsernya makna itu sendiri, yang menghasilkan
relativisme yang sangat ekstrem.
Roger Scruton, filsuf Inggris dan profesor filsafat pada universitas di
Boston, dalam naskahnya tahun 1994 Modern Philosofhy, An Introduction and
Survey, menghantam Derrida dan orang lain karena takut akan relativisme moral; dengan
membuktikan bahwa semua hukum dan larangan, semua makna dan nilai, semua yang
menyulitkan, melingkupi atau membatasi kita dalam penemuan diri kita sendiri, setan
memperkuat kepercayaan bahwa segala sesuatu diperbolehkan, kalau begitu godaan
menjadi seorang pembebas tak terelakkan.
Dengan ‘setan’ ia memaksudkan kekuatan penipuan dan penghancuran, ‘bapa
segala dusta’. Ia terus menyerang dekonstruksi sebagai tidak bertanggung jawab;
tidak memiliki makna otoritatif tunggal; ada ‘permainan bebas makna’ dan segala
sesuatu berlalu. Singkatnya kita dibebaskan dari makna.
Serangan Scruton barangkali mengungkapkan bias analitis-filosofis Anglo-Saxon
terhadap Eropa daratan. Ia melangkah terlalu jauh, paling sedikit, ia salah
memahami Derrida. Derrida tidak pernah berjuang untuk membuang rasio atau makna.
Ini hanya masalah keseimbangan, dan pemberian ruang pada yang emosional dan
yang tidak dapat diungkapkan dengan mudah.
Derrida tidak mengajarkan bahwa teks dapat memiliki sejumlah makna ad
infinitum seperti kita inginkah. Benar, teks dapat dibaca dengan cara berbeda-beda,
tetapi ada sejumlah tafsiran tertentu yang mungkin. Maksud penulis yang
disadari, keprihatinan sosial dan ideologi zaman, demikian pula pengalaman kita
dalam membaca dan bereaksi terhadap teks, semua ikut berpengaruh.
Maka, apa yang sesungguhnya yang sedang kita baca? Hendaknya kita sadar, kata
Derrida. Ia tidak menghancurkan makna. Kalau ada sesuatu yang ia lakukan, maka
itulah yang membebaskan teks dari agenda atau ideologi mana pun. Ia mengatakan,
“mari kita lihat, apa yang dapat ditemukan dalam teks’.
Derrida menegaskan bahwa metode dekonstruksinya merupakan kegiatan cinta, yang
mendorong keluar kebenaran yang jujur dan mengakui posisi yang berbeda-beda. Mengapa
kita harus percaya hanya pada apa yang dikatakan untuk kita percaya, atau
bertindak seperti yang dikatakan kepada kita.
Kepedulian Postmodern
Banyak pemikir postmodern aktif secara politis dan melibatkan diri dalam
masalah etika. Hal ini tampaknya membantah tuduhan relativisme moral, yang
biasanya diarahkan pada postmodernisme.
Derrida prihatin mengenai isu perdamaian dan keadilan, dan berbicara
tentang dekonstruksi sebagai kegiatan keramahan, dalam arti mengungkapkan
selamat datang kepada ‘yang lain’ tidak pandang yang lain, tafsiran yang lain. Keadilan
adalah kategori yang menolak dekonstruksi terakhir; bisa saja ada ide yang
berbeda-beda tentang apa itu adil, tetapi ‘yang adil’ memang ada. Keadilan
menuntut hak kemanusiaan kita.

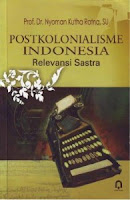

Komentar