Biaya Sekolah Diserahkan Pasar
Judul Buku : Sekolah Bukan Pasar
Penulis : St. Kartono
Penerbit : Kompas
Cetakan : Pertama, Juni 2009
Tebal : 221 halaman
“Ada
jarak sangat jauh bagi kita untuk mencapai kondisi di mana ada kesempatan yang
sama bagi setiap orang untuk menikmati setiap jenjang pendidikan dalam sistem
pendidikan” Joseph A Soares (Penulis Buku The Power of Privilege, Yale and America’s Elite College)
Pendidikan tinggi bermutu
membutuhkan pembiayaan mahal. Tidak heran pada tahun 2009, untuk masuk
perguruan tinggi sekaliber UGM, setiap semester mahasiswa harus membayar Rp 1,58
sampai 1,85 juta, ITB Rp 2,7 sampai Rp 3,7 juta, dan Unpad 2,5 juta. Biaya ini
berlaku bagi mereka yang lolos Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN), berbeda
dengan mereka yang melalui jalur Seleksi Masuk jalur khusus dengan harus
membayar sumbangan puluhan hingga ratusan juta, tergantung jurusan yang diambil.
Seperti Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) pada Fakultas Kedokteran
dengan sumbangan minimal Rp 175 juta, sementara Fakultas Peternakan, Sastra dan
MIPA memasang harga minimal Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. Fakultas lain, seperti Hukum dan
Ekonomi minimal sumbangan sekitar Rp 30 juta.
Selanjutnya, yang patut menjadi pertanyaan adalah benarkan PTN yang mahal
pasti bermutu? Bisakah kemahalan PTN itu dibebankan kepada masyarakat, sementara
pemerintah cuci tangan begitu saja? Siapa lagi yang dapat menghentikan laju
kemahalan itu? Dengan alasan kekurangan dana, pemerintah mengibarkan otonomi
PTN yang ditandai dengan perubahan status menjadi BHMN (Badan Hukum Milik
Negara) yang selanjutnya dirubah BHP (Badan Hukum Pendidikan). Otonomi itu
bukan hanya dengan membuka kesempatan seluas-luasnya untuk pihak swasta di
dalam dan luar negeri menawarkan jasa pendidikan, tetapi juga membiarkan PTN
mencari dan menghimpun dana dari masyarakat. Dengan berbagai dalih, PTN yang
selama ini diunggulkan dengan program-program khusus seperti program
internasionalisasi, menyejajarkan kompetisi kecerdasan dengan kompetisi duit. Dukungan
masyarakat hanyalah diterjemahkan dengan menarik biaya tinggi.
Menurut penulis buku Sekolah Bukan Pasar ini, St. Kartono, ketika PTN tidak
perlu menjadi tanggungan negara, cukup diberikan kepada mekanisme pasar. Disitulah
PTN berangsur-angsur menjadi tempat eksklusif yang memberikan pelayanan hanya
kepada mereka yang mampu membayar. PTN yang dicita-citakan oleh negara untuk
memberikan kesempatan pendidikan yang murah bagi kebanyakan anak negeri ini, toh
akhirnya yang menikmati adalah kalangan atas.
Konsekuensi lebih lanjut dari kebijakan otonomi tersebut adalah biaya
pendidikan di PTN menjadi melangit, sehingga peluang bagi orang miskin untuk
masuk ke PTN semakin sempit. Memang betul, argumen yang dikemukakan oleh para
pengelola PTN bahwa mereka menerapkan konsep subsidi silang agar tetap bisa
memberikan ruang bagi kaum miskin masuk ke PTN. Tapi sesudahnya, berapa besar
jumlah mahasiswa yang mensubsidi dan berapa besar jumlah mahasiswa yang
mendapat silangan sibsidi? Yang sering muncul ke permukaan, banyak kasus calon
mahasiswa menggugurkan niatnya masuk ke PTN terkemuka setelah dirinya
dinyatakan lulus tes hanya karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar uang
masuk yang dinilai cukup tinggi.
Konsep subsidi silang yang dikemukakan oleh para pengelola PTN tidak pernah
jelas, sehingga sering hanya dinilai untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan
mereka yang cenderung lebih kuat untuk akumulasi kapital saja. Tes masuk model
jalur khusus ditempuh bukan dalam rangka untuk menjaring bibit yang berbobot, tapi
untuk menjaring modal yang tinggi dari calon mahasiswa.
Mahasiswa yang masuk melalui jalur khusus ini diwajibkan membayar uang
masuk di atas puluhan juta. Bahkan, di ITB ada yang bersedia membayar uang
masuk mencapai ratusan juta. Tapi tidak pernah ada pengumuman secara terbuka
nomor-nomor tes yang diterima melalui jalur khsus beserta besarnya sumbangannya.
Yang muncul di media massa hanya mengatakan secara umum, bahwa mereka yang
diterima melalui jalur khusus tidak lebih dari 60%, sedangkan 40% persen
melalui jalur reguler dan PMDK.
Padahal jelas, yang terjadi di PTN di Indonesia sekarang ini suatu ironi.
Ketika bangsa Indonesia sedang dalam keterpurukan dan untuk mengentaskannya
dibutuhkan pendidikan yang baik, yang terjadi justru pendidikan tinggi semakin
dibuat mahal sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya saja. Ironisnya
lagi, apa yang disebut otonomi PTN itu hanya sebatas pembiayaan saja, sedangkan
kebijakan lainnya, termasuk kurikulum, tidak otonom; terbukti masih ada
Kurikulum Nasional. PTN tidak bisa otonom dalam menentukan kurikulum yang akan dikembangkannya.
Di Amerika Serikat, universitas-universitas swasta tidak punya kaitan dengan
pemerintah, selain bahwa mereka mendapat bantuan dari negara bagian atau
kotapraja, namun tidak diawasi atau diatur secara ketat, dan universitas-universitas
itu pun tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat.
Yang terjadi di Indonesia, PTN dipersilakan menggali dana sendiri dengan
boleh berbisnis, tapi seluruh kebijakan universitas, termasuk pengangkatan
dosen, penentuan kurikulum dan sebagainya, dilakukan oleh pemerintah. Ironisnya
lagi, tidak muncul perlawanan sedikit pun dari para akademisi di PTN. Perlawanan-perlawanan
yang terjadi hanya dilakukan oleh para mahasiswa yang keberatan dinaikkan SPP-nya.
Padahal, substansi masalahnya tidak sekedar biaya pendidikan di PTN menjadi
mahal, tapi menyangkut soal visi dari PTN itu sendiri. Sebab dalam praktiknya, sulit
sekali menggabungkan visi pencerdasan dengan visi bisnis. Bila PTN ditekan
untuk mandiri secara ekonomis, maka konsekuensi logisnya adalah mengembangkan
usaha bisnis. Dengan demikian, misi pencerdasan masyarakat, termasuk masyarakat
miskin, sulit untuk dilakukan.
Buku ini juga memperlihatkan berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang
kurang memihak terhadap kaum miskin. Seperti kebijakan pemerintah terhadap BHP,
menurut Kartono kebijakan ini bukanlah bentuk otonomi PTN, tapi privatisasi. Meskipun
Dirjen Pendidikan Tinggi selalu menolak sebutan BHP sebagai bentuk privatisasi,
tapi dalam praktiknya terjadi privatisasi pengelolaan PTN. Karena bentuknya
privatisasi, maka konsekuensinya, mereka yang memiliki modal besarlah yang
dapat mengakses PTN yang telah diprivatisasi. Ini jelas berlawanan dengan visi
pencerdasan bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Bila pemerintah
saja melupakan misi pencerdasan bangsa, lalu siapa yang harus menjalankan misi
pencerdasan kepada masyarakat miskin?
*) Tulisan ini dimuat di Koran Jakarta, 30 Juli 2009

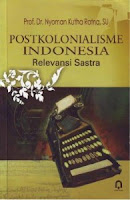

Komentar