Problem Pemekaran Daerah
Judul Buku : Pemekaran Daerah; Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi
Penulis : Tri Ratnawi
Penerbit : Pustaka Pelajar
Cetakan : Pertama, Februari 2009
Tebal : xiii + 284 halaman
Buku ini merupakan tinjauan
umum pemekaran daerah di Indonesia
di era reformasi (1999-sekarang), problematika yang dihadapi serta alternatif
pemecahan masalahnya. Dalam pandangan Tri Ratnawi, pemekaran daerah di
Indonesia secara besar-besaran sehingga berubah menjadi semacam ‘bisnis’ atau
‘industri’ pemekaran saat ini, tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan
normatif-teoritis seperti yang tersurat dalam peraturan pemekaran wilayah atau
dalam teori-teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan demokrasi lokal, memaksimalkan
akses publik ke pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan
pelayanan publik sebaik dan seefesien mungkin.
Sebaliknya, tujuan-tujuan
politik-pragmatis seperti untuk merespons separatisme agama dan etnis, membangun
citra rezim sebagai rezim yang demokratis, memperkuat legitimasi rezim yang
berkuasa, dan karena self-interest dari para aktor daerah dan pusat, merupakan
faktor-faktor yang lebih dominan, politisasi dan pragmatisme dalam pemekaran
wilayah seperti itulah yang akhirnya menimbulkan banyaknya masalah atau
komplikasi di daerah-daerah pemekaran, daerah induk dan juga di pusat.
Saat ini negara Indonesia
berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa dan bersifat majemuk dalam hal etnis, bahasa
daerah, agama, budaya, geografi, demografi, dan lain-lain. Terdapat sekitar 656
suku di seluruh Nusantara di mana 1/6 di antaranya sekitar 109 suku tinggi di
Indonesia Barat (Jawa dan Sumatra) dan selebihnya di Indonesia Timur menurut
garis Wallacea. Pengelompokan etnis tersebut sering kali bertindihan dengan pengelompokan
agama. Misalnya, etnis Ambon umumnya beragama Kristen dan etnis Bugis sebagaian
besar beragama Islam.
Sehubungan dengan itu kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah masa
reformasi merupakan kebijakan yang tepat untuk merespons keragaman tersebut. Pemekaran
wilayah merupakan salah satu aktualisasi dari kebijakan itu yang terbukti
kemudian peluang ini banyak ditangkap atau dimanfaatkan daerah dan elit-elitnya.
Dari tahun 1999 hingga akhir tahun 2006 di Indonesia terbentuk 7 provinsi baru,
129 kabupaten baru dan 26 kota baru. Hingga April tahun 2007 jumlah provinsi di
Indonesia adalah 33 buah di samping adanya 457 kabupaten/kota. Jumlah ini belum
termasuk 8 daerah baru yang disetujui oleh Presiden dan DPR pada 17 Juli 2007
untuk dibentuk. Kedelapan daerah baru tersebut adalah Kota Serang (Jabar), Kabupaten
Kubu Raya (Kalbar), Kabupaten Manggarai Timur (NTT), Kabupaten Tana Tidung (Kaltim),
Kota Tual (Maluku), Kabupaten Pesawaran (Lampung), Kabupaten Padang Lawas (Sumut),
dan Kabupaten Padang Lawas Utara (Sumut) (Depdagri 2007).
Penambahan kedelapan daerah sebagai daerah pemekaran baru ini menimbulkan
pertanyaan bagi Ratnawi mengenai konsistensi Pemerintah tentang perlunya
‘moratorium pemekaran daerah’. Bila dihitung, maka jumlah daerah pemekaran saat
ini berjumlah sekitar 5 kali lipat dibandingkan keadaan di masa Orde Baru dan
setara dengan pemekaran wilayah yang terjadi pada periode 1956-1960.
Selain itu, pada 2006 Depdagri juga telah mendaftar sekitar 110 usulan
pembentukan kabupaten/kota baru dan 21 usulan pembentukan provinsi baru antara
lain usulan calon Provinsi Tapanulis, usulan calon Provinsi Bogor, usulan calon
Provinsi Cirebon, usulan provinsi Madura, usulan calon Provisi Kalimantar Utara,
usulan Provinsi Luwu, usulan calon Provinsi Buton, usulan calon Provinsi Papua
Tengah dan usulan calon Provinsi Maluku Tenggara (Depdagri 2007). Data ini
mengarahkan Ratnawi pada ‘kecurigaan’ bahwa pemekaran wilayah memang telah
dijadikan ‘bisnis’ atau ‘industri yang menggiurkan elit-elit Pusat dan elit-elit
lokal.
Maraknya pemekaran wilayah ini di satu pihak perlu disyukuri karena memberi
tempat bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal, sesuatu yang diabaikan
oleh Orde Baru. Namun di lain pihak, fenomena pemekaran wilayah secara besar-besaran
tersebut sekaligus cukup mengkhawatirkan mengingat banyak proposal pemekaran
yang diwarnai oleh self-interest dari elit-elit lokal pengusungnya-misalnya karena
ingin menjabat di birokrasi lokal atau DPRD, ingin lepas dari himpitan
‘penindas’ kelompok etnis/agama lain, ingin membangun kembali sejarah dan
kekuasaan aristokrasi lama yang pernah pudar di masa Orde Baru.
Pembajakan atau manipulasi pemekaran oleh elit-elit lokal (‘para penunggang
gelap’) ini kemudian memunculkan banyak konflik dan masalah di tingkat lokal
termasuk masalah yang muncul pasca pemekaran, baik di daerah pemekaran maupun
di daerah induk. Di samping itu banyaknya pemekaran daerah juga dikhawatirkan
dapat meningkatkan semangat etno-nasionalisme orang-orang daerah dan sebaliknya
dapat mengurangi semangat kebersamaan sebagai bangsa Indonesia.
Mengingat proposal pemekaran
daerah sebelum dinilai ‘lulus’ di tingkat Pusat telah dibaca, dikaji dan
akhirnya di setujui oleh Pemerintah Pusat Presiden dan DPR, maka penanggung
jawab pertama atas munculnya banyak permasalahan di daerah-daerah pemekaran
adalah Pemerintah Pusat itu sendiri. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
tampaknya belum sepenuhnya dapat diminta ‘pertanggungjawabannya’ mengingat
perannya yang kurang signifikan dalam pengambilan keputusan pemekaran akibat
dari sangat kecilnya peran DPD yang diatur oleh UUD 1945 amandemen IV dan UU
Susduk No. 22 Tahun 2003.
Hasil studi dari tim Bank
Dunia menyimpulkan ada empat faktor utama pendorong pemekaran wilayah di masa
reformasi yaitu: Pertama, motif untuk efektivitas administasi pemerintahan
mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan
ketertinggalan pembangunan; Kedua, kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa,
agama, urban-ruraal, tingkat pendapatan); Ketiga, adanya kemanjaan fiskal yang
dijamin oleh Undang-undang disediakannya dana alokasi umum, bagi hasil dari
sumber daya alam dan disediakannya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah; Keempat,
motif pemburu rente (bureaucratic and political rent-seeking) para elit.
Disamping itu masih ada satu
motif ‘tersembunyi’ dari pemekaran daerah, yang oleh Tri Ratnawi di sebut
sebagai gerrymander, yaitu usaha pembelahan/pemekaran daerah untuk kepentingan
parpol tertentu. Contohnya adalah kasus pemekaran Papua oleh pemerintahan
Megawati (PDIP) dengan tujuan untuk memecahkan suara partai ‘lawan’ (hal.15). Buku
ini selayaknya menjadi kajian segar dalam memperkaya khazanah wacana politik
lokal di negara kita tercinta, Indonesia.
*) Tulisan ini dimuat di
Kabar Indonesia, 1 April 2009

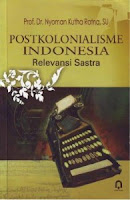

Komentar