Pertaruhan Multikultural Jogja
Judul Buku : Kekuasaan sebagai Wakaf Politik; Manajemen Yogyakarta kota
multikultur
Penulis : Herry Zudianto
Penerbit : Impulse dan Kanisius, Yogyakarta
Cetakan : I, 2008
Tebal : vii + 167 halaman
Kota Yogyakarta yang berdiri
sejak tahun 1756, telah mengalami perjumpaan dengan agama-agama besar di dunia,
seperti Hinduisme dan Budhisme, Islam dan Kristen. Juga dengan budaya-budaya
besar dari luar, seperti Eropa, Cina, Arab, dan India, kemudian disusul budaya-budaya
dari berbagai wilayah nusantara.
Dalam kurun waktu dua
setengah abad itu Kota Yogyakarta bertumbuh pelan-pelan menjadi sebuah kota dengan basis budaya Jawa dan Kraton Ngayogyakarta
Hadiningrat yang terbuka dan inklusif bagi kultur yang lain, dan oleh karena
itu kemudian menjadi pusat kekaguman dunia sebagai kota budaya.
Selain itu dalam
perjalanannya Kota Yogyakarta juga memiliki predikat sebagai kota pendidikan dan city of tolerance. Kedua predikat ini
saling berhubungan satu sama lain dalam membentuk multikulturalisme Yogyakarta.
Sebagai kota pendidikan, Yogyakarta memiliki pengalaman multikultural yang
panjang dan teruji, terutama dalam kontak dengan budaya lain yang datang
bersama dengan para pelajar dan mahasiswa dari berbagai pelosok nusantara untuk
belajar di Yogyakarta.
Maka, hakikat dan kualitas toleransi yang dimiliki kota Yogyakarta pun
banyak ditentukan oleh relasi-relasi intelektual. Sendainya Kota Yogyakarta
adalah kota industri maka pola-pola interaksi sosial dan bentuk-bentuk
toleransi yang dihasilkan pun akan berbeda.
Warga Yogyakarta memandang predikat city of tolerance yang disandang
mempunyai kontribusi terhadap berbagai prestasi yang diraih kota ini. Toleransi
yang berarti ada harmoni, saling pengertian, dan kesediaan untuk saling
menerima, saling mengikuti dan mau bekerja sama. Karena itu toleransi dalam
kontek ini mengandung makna yang lebih luas melampaui pengertian toleransi
antar suku/etnis, agama dan kebudayaan.
Toleransi dalam konteks ini menyentuh aspek struktur sebuah masyarakat di
mana tidak ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang tidak dijembatani di dalam
masyarakat yang dapat memicu konflik antarkelompok masyarakat. Karena semangat
toleransi dalam pengertian ini pula maka para warga, tanpa membedakan status dan
kelas sosial, bisa memiliki tingkat kekompakan yang tinggi dalam menjaga
ketertiban, kebersihan dan keindahan kota sebagai tanggung jawab bersama.
Penghargaan terhadap Kota Yogyakarta sebagai satu-satunya kota yang
berhasil menangani pemukiman kumuh, juga penghargaan adipura dan sanitasi-semuanya
bisa tercapai tiada lain karena semua warga kota dari berbagai latar belakang
etnis/suku, agama, afiliasi politik, dan kelas sosial itu kompak, satu tindakan
bersama-sama dengan pemerintah kota untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang
bersih dan nyaman.
Berangkat dari cara pandang di atas, realitas multikultural Kota Yogyakarta
tidak hanya menyangkut pengakuan dan memperhitungkan keragaman etnis/suku, bangsa,
agama, kebudayaan, aliran politik, dan sebagainya tetapi juga keberagaman kelas
sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, profesi, cara pandang, kebiasaan-kebiasaan
sehari-hari, dan sebagainya, singkatnya semua komponen masyarakat Kota
Yogyakarta dengan segala realitas kehidupan mereka. Dengan demikian tidak ada
kelompok masyarakat yang merasa dipinggirkan dan tidak mendapat perhatian yang
layak dari pemerintah kota dan masyarakat lain.
Sejalan dengan itu semua, kehadiran buku ini yang ditulis Herry Zudianto
menurut saya tidak saja ingin mengangkat kegundahan seorang pemimpin dalam
menatap dan menata kebijakan sebuah kota yang multikultural; juga bukan ratapan
atas kehilangan jati diri masyarakat Yogyakarta yang sesungguhnya amat
menjunjung tinggi filosofi teposeliro. Buku ini, dalam segala kekurangan dan
kelebihannya, menawarkan persepektif tersendiri dalam melihat dimensi-dimensi
kehidupan sosial yang amat mendasar dan penting dalam menjaga dan merawat
kebersamaan.
Salah satu persoalan yang amat penting dalam buku ini adalah bagaimana
mengelola perbedaan dengan cara-cara demokratis, dialogis dan santun sesuai
tatakrama kultur yang mengakar. Jika paradigma resolusi konflik pada umumnya
mengedepankan pengelolaan perbedaan, maka buku ini menawarkan sebuah pradigma
khas; bagaimana mengelola kesamaan untuk merawat kebersamaan agar tidak
terkikis oleh wacana-wacana dikotomis yang dibawa oleh perbedaan.
Keberanian dan kemampuan untuk melihat kesamaan-kesamaan yang dimiliki
seseorang atau sekelompok masyarakat dengan pihak lain berfungsi sebagai filter
untuk tidak serta-merta memandang mereka yang lain dengan segala perbedaan
mereka itu sebagai lawan. Sebaliknya, kemampuan mengindentifikasi kesamaan-kesamaan
berfungsi sebagai langkah etis untuk menghargai perbedaan tanpa niat untuk
mengubah mereka yang lain agar menjadi sama dan seragam sesuai dengan kemauan
kita (hal.152).
Kesamaan yang hendak diidentifikasi itu juga melampaui pengertian kesamaan
identitas. Dialog dan masalah etika komunikasi sebagai syarat demokrasi, sebagaimana
digali dan diangkat ke permukaan dalam buku ini, menjadi inspirasi yang amat
berharga untuk menyebut apa itu kesamaan: kesamaan atau kesetaraan sebagai
patner dialog yang tetap menjunjung tinggi sikap respek terhadap martabad
manusia dan posisi sosial masing-masing; kesamaan dalam semangat mencari titik
temu dalam memecahkan persoalan yang ditimbulkan oleh perbedaan cara pandang; dan
kesamaan untuk mau berubah secara bersama-sama.
Kesamaan-kesamaan dalam pengertian ini lebih dari sekedar kesamaan yang
diwariskan, melainkan kesamaan dinamis, kesamaan yang terus-menerus diupayakan
untuk menemukan common platform dalam rangka membangun kesepakatan-kesepakatan
bersama.
Jika ada yang dapat disebut
sebagai kegelisahan dalam buku ini maka kegelisahan itu adalah gejala mulai
menguatnya indivialisme yang telah menggerogoti hampir semua aspek kehidupan
warga Kota Yogyakarta. Semangat individualisme pribadi maupun kelompok telah
mengancam wajah Kota Yogyakarta menjadi kapitalis, individualis, dan
materialistis, jauh dari filosofi teposeliro dan humanisme. Kegelisahan dalam
buku ini adalah kegelisahan seorang warga kota (citizen)
yang kebetulan menjadi walikota yang bertanggung jawab mengelola tata kehidupan
sebuah komunitas masyarakat warga (society) dalam kota.
*) Tulisan ini dimuat di Majalah Flamma, April-Juni 2009

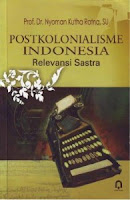

Komentar