Mengkaji Islam dalam Keberagaman
Judul Buku : Mengindonesiakan
Islam; Representasi dan Ideologi
Penulis : Dr. Mujiburrahman
Penerbit : Pustaka Pelajar
Cetakan : Pertama, Desember 2008
Tebal : xxiii + 438 halaman
Kenyataan bahwa Indonesia
adalah bangsa yang sangat beragam merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri
oleh siapa pun. Keragaman Indonesia
tidak saja tercermin dari banyaknya pulau yang dipersatukan dibawah kekuasaan
satu negara, melainkan juga keragaman warna kulit, bahasa, etnis, agama dan
budaya. Tapi kemudian yang menjadi persoalan bukanlah kenyataan bahwa bangsa
ini adalah amat beragam, melainkan cara kita memandang dan mengelola keragaman
tersebut.
Para pendiri bangsa ini jelas sangat menyadari akan masalah keragaman ini. Pertanyaan
mereka saat mendirikan negara ini adalah atas dasar apakah kiranya segala yang
beraneka ragam itu dapat dipersatukan? Sejarah mencatat bahwa ada dua jawaban
yang berbeda terhadap masalah ini. Satu kelompok mengatakan bahwa kita bisa
bersatu atas dasar “kebangsaan” dan satu kelompok lagi mengatakan bahwa kita
bersatu atas dasar “agama”, yakni agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa
ini.
Sejarah bangsa ini juga penuh dengan catatan mengenai dialektika yang terus-menerus
terjadi antara paham kebangsaan di satu pihak dan paham keislaman di pihak lain.
Dialektika itu kadang bahkan berujung pada tindakan kekerasan yang berdarah-darah,
tetapi kadang pula terjadi suatu sintesis dan integrasi secara damai.
Buku ini hadir dari kumpulan tulisan yang membahas berbagai permasalahan
sosial keagamaan, baik pada tataran pemikiran ataupun kemasyarakatan. Di antara
masalah kontroversial yang diangkat Mujiburrahman yaitu debat soal pluralisme, negara
versus negara Pancasila, dan isu-isu seputar kebebasan beragama dan demokrasi. Dalam
hal pluralisme, Muji menilai kontroversi ini terjadi setelah MUI mengeluarkan
fatwa tahun 2005 yang lalu bahwa pluralisme bertentangan dengan Islam. MUI
mendefinisikan pluralisme sebagai pandangan yang menganggap semua agama sama
dan dapat membawa kepada keselamatan.
Dalam hingar bingar perdebatan mengenai masalah ini, Muji tidak secara
langsung menolak pandangan MUI. Dalam kenyataan memang ada sebagian pemikir
yang punya pandangan pluralisme teologis seperti yang didefinisikan MUI itu. Tetapi
bagi Muji, debat teologis akan menghabiskan energi karena kita akan sulit
menemukan kesepakatan. Persoalan yang lebih penting justru terletak pada
tataran sosial. Kerena itu, Muji mengusulkan pluralisme diartikan sebagai sikap
yang positif terhadap keragaman, dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengelola
keagaman itu secara damai dan berkeadilan (hal.44). Dengan demikian, sikap
saling menerima dan bekerjasama dapat dikembangkan tanpa harus mengorbankan
klaim teologis dari masing-masing agama.
Berkenaan dengan masalah negara Islam versus negara sekuler, berdasarkan
analisis sosial historis, Muji berpendapat bahwa kompromi yang dibuat oleh para
pendidik bangsa ini, yakni bahwa Indonesia adalah bukan negara Islam, bukan
pula negara sekuler yang tercermin dalam Pancasila, terutama sila pertama, Ketuhanan
Yang Maha Esa, adalah suatu kompromi politik yang harus dipertahankan jika kita
masih ingin mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Debat tak
berkesudahan antara kubu Islam dan sekuler yang terus berkembang hingga saat ini,
menurut Muji, tidak akan dimenangkan secara politik oleh pihak manapun. Di sisi
lain nilai-nilai moral Pancasila seperti kemanusiaan dan keadilan dapat
dijadikan pijakan bersama bagi upaya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman/keagamaan
dengan nilai-nilai kebangsaan. Karena itu, jalan yang lebih realistis adalah
menerima dan mengembangkan kompromi yang sudah ada untuk memecahkan problem-problem
yang tengah kita hadapi.
Sebagai ilustrasi mengenai kemungkinan mengembangkan kompromi tersebut
adalah kompromi dalam merumuskan kebijakan mengenai isu-isu kebebasan beragama.
Kalau kita mau mendapatkan kebebasan beragama yang tuntas, barangkali hanya
negara sekuler yang dapat mewujudkannya. Tetapi Indonesia memang bukan negara
sekuler, tapi juga bukan negara Islam. Di Indonesia, ada kebijakan mengenai
agama-agama yang diakui dan tidak, dan ini dinilai bertentangan dengan
kebebasan beragama. Tetapi adakah kiranya suatu jalan keluar kompromi? Berdasarkan
teks resmi pemerintahan tahun 1965, di buku ini Muji mengajukan pertanyaan; bisakah
kiranya pemerintahan memberikan bantuan finansial dan perlindungan kepada agama-agama
yang diakui, dan pada saat yang sama memberikan perlindungan saja kepada agama/kepercayaan
yang tidak diakui?
Kompromi yang sama Muji ajukan berkaitan dengan masalah perkawinan. Undang-Undang
Perkawinan 1974 merumuskan sahnya perkawinan berdasarkan agama. Dalam hal ini
umat Islam dapat melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam dan sekaligus
disahkan negara. Tetapi masalah kemudian muncul karena hanya berdasarkan agama
yang diakui yang dianggap sah. Selain itu, kawin antaragama umumnya dianggap
tidak sah oleh para ahli agama sehingga perkawinan seperti ini sulit untuk
dilegalkan. Di sini Muji bertanya; bisakan perkawinan di luar agama yang diakui,
dan perkawinan antaragama, disahkan melalui catatan sipil saja?
Sisi lain yang menarik dari buku ini adalah selain mendiskusikan beberapa
upaya yang telah dilakukan oleh para cendekiawan kita dalam rangka membangun
hubungan kerja sama antara berbagai agama. Penulis juga mencoba mengkaji
bagaimana pra ulama Sunni di Abad pertengahan mencoba mencari titik temu dalam
rangka menyingkapi perbedaan dan pertentangan teologis intra-umat Islam sendiri.
Disini kita diajak untuk berdialektika dalam wacana konflik-konflik sosial
keagamaan yang pernah terjadi, paling tidak kita dapat memahami dan mengambil
manfaat dalam membangun kebersamaan di masa sekarang dan akan datang.
*) Tulisan ini dimuat di Majalah Suluh, Maret-April 2009

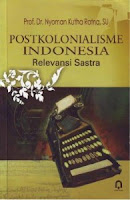

Komentar