Bali dan Pradoks Masyarakat Lokal
Judul Buku : Bali yang Hilang; Pendatang, Islam dan Etnisitas di Bali
Penulis : Yudhis M. Burhanuddin
Penerbit : Impulse dan Kanisius
Cetakan : Pertama, 2008
Tebal : 213 halaman
Bali tempo dulu dan bali masa kini adalah dualisme paradoks wajah Bali
yang hendak dikemukakan dalam buku ini. Dengan merujuk sejarah kerajaan Jawa-Bali
dan karya-karya etnografis tentang Bali dari antropolog asing, wajah Bali tempo
dulu digambarkan penuh gairah dan pesona. Orang Bali, alam, budaya, dan
agamanya dalam khazanah pariwisata lebih menjadi objek daripada subjek karena
pertautan keempatnya semata-mata merupakan aset pariwisata Bali.
Antropolog Barat misalnya, menemukan Bali sebagai sebuah pulau, dimana
budaya dan alam saling berpautan erat, tempat tinggal sebuah masyarakat mapan
dan harmonis yang secara berkala digairahkan ritus-ritus yang memesona. Alamnya menyajikan keindahan Bali dalam warga gaib
tridatu dan kilauan sunset dewata nawa sanga yang menggetarkan rasa-agama-budhi.
Kebudayaan Bali yang diwarnai pernik-pernik yadnya menawarkan keramahan orang
Bali khas Bhakti dalam tatanan dan tuntunan santun sarat pesona melalui jalinan
tattawa-susila-acara. Keterpaduan antara kelimpahan upacara, kesenian dan
pemandangan hijau menggambarkan ciri arkais kebudayaan Bali.
Melimpahnya kegiatan ritual
dan seni orang Bali menurut Mead dan Bateson (Picard, 2006) patut dilihat
sebagai gejala yang harus dibahas dalam kerangka psikologis-kultural. Di mata
mereka, kebudayaan Bali menjadi semacam sistem pengatur dorongan-dorongan
naluri yang menimbulkan sejenis skizofrenia-kultural. Pada kenyaannya, dalam
pengalaman empiris kehidupan sehari-hari jalinan antara agama Hindu dan
kebudayaan Bali telah menjadi panduan bagi sikap dan perilaku orang Bali. Dengannya
orang Bali membentuk suatu keyakinan. Kebudayaan itu merupakan blue-print
karena kebudayaan itu dijadikan pedoman tingkah laku. Religius dalam bingkai
yadnya telah melahirkan harmoni kehidupan mengagumkan sehingga Bali layak
dijadikan objek pemuas selera manusia modern.
Bali masa kini merupakan
gambaran sebaliknya, dengan diwakili dua wajah pariwisata Bali sekitar kawasan
Kuta (Samingita: Seminyak-Legian-Kuta) dan Sanur, Badung dan Denpasar. Coreng-moreng
iklan dan reklame menghiasi ruang-ruang publik, ekpresi “kebinatangan” manusia
jalanan dalam carut-marut lalu lintas jalan raya, pojok-pojok remang-remang
pertamanan kota, adu nasib lewat ayam-ayam jago, adu takdir melalui nomor-nomor
gelap, tawar menawar harga diri sepanjang sisi gelap jalanan, dan sudut-sudut
kafe kapitalistik melengkapi gambaran buram wajah Bali pada masa kini. Bali
yang renta dalam semangat-keperkasaannya, lusuh dalam kegairahannya, dan lesu
dalam ketegarannya.
Tegangan paradoks ini, seperti
fisik-psikis atas-bawah, dan pusat-pingirang menjadi gaya pengungkapan Yudhis M.
Burhanuddin dalam buku Bali yang Hilang; Pendatang, Islam dan Etnisitas di Bali
ini, tentang implikasi psiko-sosio-budaya pariwisata Bali pascabom Kuta
terhadap pendatang dalam pergulatan keagamaan dan etnisitas. Pada kawasan Sanur
dan Kuta, ketiga konsep utama digambarkan pada posisi paradoks, antara
pendatang dan penduduk asli, Islam dan Hindu, serta etnisitas dan nasionalitas.
Pada dasarnya ini merupakan pengungkapan fungsi laten pariwisata Bali pascabom
Kuta, antara lain meliputi tanggapan dan sikap orang Bali-konservatif, moderat,
dan progresif-terhdap pendatang dalam konteks keagamaan dan etnisitas.
Penelusuran serius dan
sungguh-sungguh melalui ide-ide kesejarahan dan eksplorasi kancah yang mendalam-yang
menurut penulis peneliti teoretis-akademis-paling tidak telah memberikan
fragmentasi pergumulan sosial dan budaya dalam pengalaman langsung antara orang
Bali dan pendatang seputar agama dan etnisitas.
Hal ini memang tampak jelas
sejak awal perbincangan yang dimulai dari bagian pertama dengan judul
Pertahankan Citra, “Gugat” Pendatang. Bagian pertama ini lebih merupakan
gamabaran paradoks antara budaya induk dan budaya jalanan. Budaya induk
digambarkan merupakan tradisi yang telah mapan dalam kultur dan struktur yang
hidup dan berkembang melalui sekaa-sekaa fungsional, banjar, dan desa pakraman.
Lembaga-lembaga adat ini dipandang sebagai citra kemapanan, seperti antara lain
keamanan dan kedamain termasuk ketenteraman, situasi mana pariwisata Bali
bersandar.
Sebaliknya, budaya jalanan
merupakan anak turunan dari budaya induk berupa “anak yang tidak diharapkan”
karena memiliki sifat-sifat yang tidak sama, bahkan secara normatif dianggap
menyimpang dari budaya induknya yang dianggap baku, formal, dan mapan. Burhanuddin
memberikan contoh suburnya perkembangan premanisme dalam dua kawasan wisata
tersebut. Di antara budaya ini pariwisata Bali dipertaruhkan karena pariwisata
lebih ditempatkan pada posisi ideologis, yakni seni bertahan hidup dan
pengumpulan kekayaan, baik bagi penduduk asli maupun pendatang. Pada dasarnya
ini merupakan dampak dari proses modernisasi dan globalisasi yang memang tidak
dapat dihindari. Ini juga mendorong terjadinya estetisasi dan komudifikasi
kehidupan secara meluas. Karena itu “perang” antara idealisme dan materialisme
tidak dapat dihindarkan.
Pengaruh modernisasi dan
globalisasi melalui industri pariwisata terhadap aspek-aspek kehidupan
masyarakat menjadi perhatian serius Burhanuddin. Dalam dua kawasan wisata, Kuta
dan Sanur, digambarkan keterpinggiran penduduk lokal akibat kalah “perang-melawan”
pendatang dalam berbagai sektor terutama sektor ekonomi. Kekalahan penduduk
lokal dari pendatang disebabkan beberapa faktor yang sekaligus menjadi indikator
perubahan karakter orang Bali, antara lain seperti berikut.
Pertama, karena
ketidaksiapan dan ketidakmampuan orang Bali untuk bersaing dengan pendatang
baru. Kedua, persaingan dan pemilihan antara kategori beroposisi telah
membentuk karakter lebih lagi sikap itu dijustifikasi melalui simbol kultural. Ketiga,
perubahan karakter orang Bali juga dipengaruhi oleh proses monetarisasi. Keempat,
banyak institusi sosial dan kultural mulai tidak mampu memerankan fungsi-fungsi
manifes, malahan cenderung hanya menjadi media untuk menghidupkan “keagungan
fisikal masa lalu”. Kelima, sekalipun wanaca mengenai pentingnya kebudayaan
sebagai “panglima” pembangunan Bali, tetapi dalam implementasinya alokasi biaya
untuk kepentingan itu belum sesuai dengan wacana dan harapan. Selain kelima
faktor eksternal tersebut perubahan karakter orang Bali juga disebabkan karena
secara internal orang Bali sendiri memiliki potensi terbuka dengan perubahan
dan mengakui perubahan itu sebagai suatu titah yang harus diikuti.
Keterbukaan orang Bali
terhadap pendatang memang tidak ada salahnya, tetapi sikat permisif yang
berlebihan pada gilirannya menimbulkan permasalahan ikutan, seperti
ketakstabilan daya dukung ruang, menurunnya kualitas ekologi, populasi penduduk
tak terkendali, persaingan hidup semakin ketat, politik identitas menjadi
bagian integral dari eksistensi diri, ruang-ruang sosial semakin padat
interaksi dan integrasi soail semu, otonomi sosial dan diferensiasi budaya
terjadi secara meluas. Implikasi ini dijelaskan dalam berbagai fenomena
perilaku menyimpang secaca psiko-sosial yang mengindikasikan terjadinya
penurunan dimensi moralitas dan humanitas.

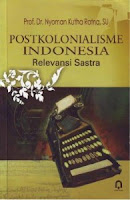

Komentar